
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak menghapus kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan dalam pertimbangannya hakim konstitusi menegaskan bahwa setiap warga negara “harus beragama atau percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Ahli kebebasan beragama menilai keputusan ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berkeyakinan.
Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan mengatakan putusan terbaru MK itu tidak lain dari sikap pemerintah memaksa warga negara menganut salah satu dari tujuh agama atau kepercayaan yang diakui pendidikan.
Kedelapan agama dan kepercayaan di dunia adalah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan penghayat kepercayaan lainnya.
Ajaran tersebut melanggar pokok dasar masyarakat yang bukan termasuk dalam tujuh doktrin utama tersebut.
“Apa yang tidak dia pilih, dia tidak akan punya KTP, tidak diakui hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Padahal itu signifikan. Itu pelanggaran serius terhadap konstitusi,” ujar Halili ketika dihubungi, Minggu (05/01).
Sebelumnya, dua warga negara telah mengajukan gugatan terhadap dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai penulisan kolom agama pada Kartu Keluarga dan KTP.
Kedua pasal itu dianggap melanggar kebebasan individu yang tidak menganut agama atau kepercayaan tertentu.
Seorang akademisi dari Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada, Mohammad Iqbal Ahnaf mengatakan tidak ada peraturan yang eksplisit melarang orang untuk tidak beragama.
Tetapi, ada banyak peraturan administratif yang memaksa seseorang untuk memeluk agama. Mulai dari saat dilahirkan, menempuh pendidikan, menikah, bahkan sampai menjadi presiden ia harus bersumpah “berdasarkan agama dan keyakinannya”.
“Jika tidak beragama, itu dianggap bertentangan dengan ketentuan. Itu menjadi salah satu alasan hakim mengambil keputusan tersebut,” kata Iqbal secara menyesal tentang putusan itu.
BBC News Indonesia berbicara dengan dua orang yang menyatakan bahwa dirinya adalah agnostik dan ateis tentang bagaimana penerapan agama mempengaruhi hidup mereka.
Mau melangsungkan pernikahan itu sendiri diribetkan dengan masalah agama saja
Aika, berusia 39 tahun, lahir dalam keluarga yang menganut agama Kristen. Ayahnya adalah seorang pendeta. Menurut Aika, keluarganya cukup setia pada tradisi.
Sejak 2013, Aika mengaku agnostik. Namun dia dipaksa masih menulis Christine dalam kolom agama di identitas dirinya (KTP-nya) sampai sekarang.
“Karena negara meminta seperti itu, jadi ya sudah, aku mengikuti saja injil agama yang pernah saya tempuh,” kata Aika.
Situasinya tidaklah sederhana itu. Di kartu identitasnya, kolom agama memainkan peran. Di antaranya, ia harus menghadapi masalah saat mengambil keputusan pernikahan.
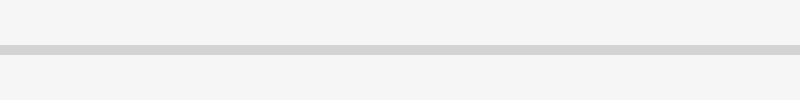
BBC News Indonesia
hadir di WhatsApp
.
untuk menjadi yang pertama mendapatkan berita, investigasi, dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung ke WhatsApp Anda.
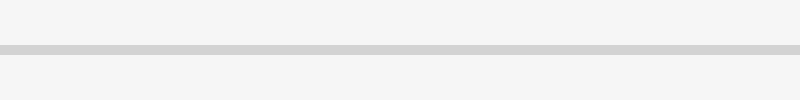
Seseorang dengan kewarganegaraan asing (WNA) yang mengaku tidak memiliki keyakinan agama sedang menjalin hubungan dengan kawannya di Indonesia. Mereka berencana untuk menikah di Indonesia, namun terdapat hukum yang melarang hal ini.
Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan merupakan sah bila dilaksanakan menurut aturan masing-masing agama dan kepercayaan.
“Saya saat ini sedang mencari rute untuk menikah di luar negeri karena saya merasa kesulitan untuk menemukan tempat di sini. Karena saya tidak memiliki koneksi di mana-mana,” ujar Aika.
Dia juga tidak mau mengorbankan nafsu sendiri dengan melangsungkan pernikahan dalam agama Kristen, contohnya.
“Itulah penutupan peluang bagi kami untuk mengesahkan pernikahan itu di Indonesia. Disini tidak bisa melangsungkan upacara pernikahan sipil saja. Jikalau pernikahan itu dianggap cukup, sesuatu yang merupakan hal memalukan bagi kami,” ujarnya.
Aika merasa negara telah memiliki perilaku diskriminatif terhadap dirinya. Dia sangat kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat intervensi negara terhadap kepercayaan warga.
“Agnostik itu juga identitasku sebagai warga negara,” pernyataannya singkatnya.
Kami dilarang mempermainkan agama, tapi ini yang dilakukan negara terhadap warga negaranya. Sesuai pikiranku, jangan marah kami karena negara yang memaksa saya memeluk-agama tertentu,” kata Aika.

Guruh Riyanto menyatakan menikah dengan mantan istrinya, yang masih mengamalkan agama Islam, dengan upacara pernikahan Katolik. Padahal, Guruh sendiri adalah seorang ateis.
“Apakah mau [seperti itu] atau tidak, karena itu pengaruhnya pada hak asuh anak. Kalau pernikahan tidak dicatatkan, anak itu menjadi milik sang ibu saja. Ayahnya tidak diakui, tidak mendapatkan hak asuh,” demikian kata Guruh.
Katolik masih dicantumkan dalam isi agama passport Guruh sampai sekarang.
“Iya, aneh sekali, di kartu keluarga anak saya harus mencantumkan agama, akhirnya saya mengisi Buddha,” ujarnya.
“Sekarang ini nanti kalau dia sudah berumur 17 tahun, dia bisa memilih agamanya sendiri. Pasalnya tidak adil kalau anaknya dipaksa menganut agama tanpa dipahami hak dan kebebasannya,” kata Guruh.
Menurutnya, pertimbangan hakim konstitusi soal konsep kebebasan beragama pada konstitusi itu “tidak masuk akal”.
Bagi Guruh, kebebasan seharusnya tidak memaksa warga negara untuk memilih di antara pilihan yang diakui oleh pemerintah.

Persoalan-persoalan lain pulalah yang dijabarkan oleh Raymond Kamil dan Indra Syahputra ketika mengecam MK untuk menghapuskan kolom agama.
Di sisi lain, orang yang tidak beragama harus mengikuti pendidikan keagamaan saat bersekolah atau kuliah.
Penggugat yang lain juga mengatakan bahwa tidak memeluk agama dan kepercayaan bukanlah pelanggaran hukum atau pidana. Alasannya, tidak ada peraturan hukum yang jelas melarang seseorang tidak memeluk agama atau kepercayaan.
Dianggap melanggar hak asasi manusia oleh beberapa pihak
Apa pertimbangan MK menolaknya?
Dalam menilai pidatohnya sudah masuk dalam pertimbangan hukumnya, hakim konstitusi mengatakan bahwa setiap warga negara “harus” menyatakan memeluk agama atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu disebut sebagai “keimanan yang diharapkan oleh Pancasila dan pidatanya diamanatkan oleh konstitusi”.
.

Arief kemudian menyatakan bahwa setiap warga negara hanya diwajibkan menyebutkan agama dan kepercayaannya untuk dicatat dan dicantumkan dalam data kependudukan tanpa ada kewajiban hukum lain yang dibebankan oleh negara.
Tenang tentang UU Perkawinan yang tidak menempatkan penduduk yang non-agama dalam perannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pernikahan tidak dapat dipisahkan dari prinsip dasar “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
“Dengan tidak memberikan ruang bagi warga negara Indonesia untuk memilih tidak menganut agama atau tidak menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka norma hukum positif yang hanya memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang dilakukan menurut norma agama dan kepercayaan masing-masing bukanlah norma yang menimbulkan diskriminatif,” kata Arief.
Setara: Kategori agama menjadi alat diskriminasi
Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan mengatakan bahwa kolom agama pada akhirnya melahirkan praktek diskriminasi dan penindasan terhadap warga negara. Oleh sebab itu, urusan sipil dan agama patut dipisahkan.
Keterlambatan pengesahan pernikahan hanya merupakan satu contoh dari banyaknya masalah. Menurut analisis yang lebih mendalam dari Halili, implikasi bahkan lebih luas dan kompleks ketika kita menganggap tentang catatan sipil yang terkait banyak hal.
“Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, asuransi, perbankan, bahkan kredit permodalan untuk usaha itu menggunakan catatan sipil,” kata Halili.
“Maka ketika kolom agama menjadi wajib, jika dia tidak memilih satu di antara tujuh itu, dia tidak akan mendapatkan KTP. Dia tidak akan diakui sebagai warga negara yang perlu menerima fasilitas dasar. Itu pelanggaran serius,” demikian kata Halili.
Baca juga:
- “Saya Yahudi, tetapi dalam KTP Islam”, penganut agama minoritas ingin diakui sehingga dapat mengakhiri ‘diskriminasi’
- Penganut kepercayaan ini secara umum akan dipasukkan dalam golongan orang-orang yang tidak mengakui atau memiliki agama tertentu.
- Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan udara segar bagi para penghayat kepercayaan dan memulihkan martabat masyarakat.
Kehadiran kekuasaan negara dalam urusan ini, kata Halili, mempunyai dampak akhirnya membuat orang-orang mengelaborasi atau mengorbankan.dirinya.doanya.post ways will berbagai cara untuk menyelamatkan diri sendiri
Kolom agama menjadi sesuatu yang “dangkal” karena dimaknai hanya sebagai urusan administratif, bukan refleksi spiritual seseorang.
“Pada lingkungan negara yang demokratis, berdasarkan agama dalam form pilihan awal itu tidak relevan. Haruslah beragama dengan hakikatnya dulu. Hendaknya lebih mudah dicapai jika negara tidak mewajibkan warganya memilih salah satu antara tujuh keyakinan,” kata Halili.
Bagaimana asal-usul kolom agama tercantum di Kartu Tanda Pengenal?
.
Sementara itu, TAP MPR Nomor 4 Tahun 1978 mewajibkan adanya kolom agama yang harus diisi salah satu dari lima agama yang(diakui) oleh pemerintah pada waktu itu.
Halili dari Setara Institute menuduh adanya kaitan antara kolom agama dan propaganda anti-komunis rezim Orde Baru setelah hapusan 1965. Menurutnya, ada unsur politik di baliknya.
Pada saat itu, yang dianggap secara keagamaan tidak jelas, itu mudah ditelanjangi oleh ideologi komunis. Narasi itu berkembang saat itu sehingga [kolom keagamaan] dianggap sebagai upaya menghambat ekspansi kelompok yang di mata rezim tetap pemicu terjadinya G30S,” kata Halili.
Juga menjelaskan bagaimana rezim Orde Baru mengidentifikasi komunisme dengan ateisme.
Pelabelan ‘atheis’ terhadap PKI kemudian menjadi alat propaganda untuk menangkap warga. Kolom agama mempermudah identifikasi.
Penamaan itulah yang pula mempengaruhi para penganutnya, yang oleh rezim Orde Baru biasanya disebutkan sebagai “kebudayaan”, bahkan bukanlah sebagai agama.
Situasinya membaik bagi penganut kepercayaan selanjutnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui gugatan mereka agar keyakinan mereka dikenali oleh pemerintah pada 2017. Penganut kepercayaan kemudian bisa menulis kepercayaan mereka di Kartu Penerbangan Identitas Penduduk (KTP).
Iqbal Ahnaf dari CRCS menyatakan bahwa kehadiran KTA dari beberapa sisi dapat dianggap sebagai kemajuan bagi ajaran keagamaan. Namun, di pihak lain, hal ini juga dapat diartikan sebagai konfirmasi dari pemerintah bahwa warga “harus” menjalankan ajaran agamanya.
Akhirnya, mereka yang tidak berafiliasi dengan agama tertentu—seperti agnostik dan ateis—masih tidak memiliki pilihan itu.
Baca juga:
- Apa saja pengertian neraka menurut agama Kristen dan agama lainnya?
- Apakah agama akan tetap ada di masa depan?
- Bebas beragama dan berkepercayaan di Indonesia 2023: Izin mendirikan tempat ibadah masih sulit
